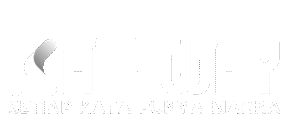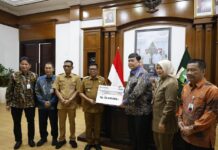Oleh Anas Al Lubab
Kini kita hidup di zaman percepatan informasi yang begitu massif tak terkendali. Setiap menit setiap detik kita digempur oleh ragam pemberitaan yang dengan mudah disebarluaskan oleh penguna setia media sosial. Baru-baru ini wajah dunia pendidikan kembali dicoreng oleh insiden seorang guru SMK di wilayah Makassar yang babak belur hingga berlumur darah setelah digepruk salah seorang wali siswa yang tak terima anaknya dikerasi.
Menurut berita yang sekilas saya baca yang belum tentu kebenarannya. Kejadian itu bermula dari teguran keras sang guru terhadap siswa yang dianggap kurang disiplin lantaran tidak mengumpulkan tugas PR-nya. Alih-alih meminta maaf atas kekeliruannya, sisiswa tersebut justru memberikan berbagai alasan dan melontarkan kata-kata sarkasme yang membuat sang guru muntab sehingga refleks menamparnya. Sianak manja yang tak terima cepat-cepat mengadu kepada orangtuanya. Terjadilah insiden berdarah di atas.
Akibat insiden tersebut, konon orangtua wali siswa harus berurusan dengan pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Sementara sianak mendapatkan sanksi moral dikeluarkan dari sekolah dan diboikot tidak akan diterima pindah di seluruh sekolah di wilayah Makassar.
Dulu sewaktu saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, nonton layar tancep di tempat hajatan saja kami tak berani. Lantaran guru-guru diberi kewenangan penuh oleh para orangtua kami untuk menempa kami dengan keras. Jika kami nekat dan ketahuan nonton, maka tangan kiri kami akan disabet mistar kayu sejumlah film yang kami tonton.
Kian banyak film yang kami tonton, pukulan sang guru biasanya kian keras (mengingat kian malam film yang diputar biasanya kian panas). Sakitnya jangan ditanya, bisa membekas dua hingga tiga hari. Tapi alih-alih berani melapor atau mengadu kepada kedua orangtua kami, jika orangtua kami sampai tahu justru akan menambahi hukuman plus kucuran nasihat hingga kami bosan mendengarkannya.
Kini, para guru di sekolah seperti macan ompong yang kehilangan cakarnya. Sebandel dan semenjengkelkan apapun prilaku siswa di sekolah, jika sudah tak tahan emosi guru hanya bisa berlalu menjauh sambil meng- elus dada. Jangankan memukul pakai mistar, atau menampar, sekadar menjewer kuping pun para guru sudah ketar-ketir dihantui perasaan was-was akan dilapor polisikan.
Entahlah kapan dan siapa yang pertama kali memulai mengkonotasinegatifkan kata kekerasan, padahal keras itu boleh dan sah, yang tidak boleh dan nggak usah adalah prilaku kekejian. Keras itu berdasarkan per- hitungan yang matang (menghitung secara detail dan teliti aspek mudarat manfaatnya), sementara kekejian merupakan respon refleks emosional tanpa per- timbangan sekaligus menegasikan sehatnya nalar.
Semua kenyataan di atas memunculkan berbagai reaksi kreatif sekaligus satir. Ada yang menyebarkan meme plus quote yang menyatakan bahwa untuk menjadi guru sekarang ini minimal mesti memiliki 3 kompetensi ijazah; ijazah keguruan, ilmu hukum, dan beladiri.
Anies Baswedan, Mendikbud yang digantikan oleh Muhadjir Effendy sebenarnya sudah memulai langkah baik dengan mewajibkan para siswa dan guru membaca buku sastra 15 menit sebelum memulai pelajaran, dan menyetop sistem perpeloncoan di Masa Orientasi Siswa (MOS) yang kini berubah wajah menjadi Pe- ngenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Rupanya Anies mengamini pernyataan Ali bin Abi Thalib yang mengisyaratkan bahwa manusia yang melek sastra akan lembut hatinya sehingga mudah mencerap cahaya ilmu dan bimbingan.
Dua kali tahun ajaran baru dapat kita simak pidato inspiratif sekaligus menerbitkan harapan yang ditulis dengan sangat literat oleh Anies Baswedan langsung, yang dibacakan oleh kepala sekolah saat hari pertama masuk siswa baru. Isinya kurang lebih himbauan agar kedepannya sekolah menjadi lingkungan yang aman dan nyaman sekaligus penuh gairah sehingga memantik percik api segenap potensi siswa. Sehingga tak memenggal sebatas leher ke atas (kognitif semata) melainkan juga menyentuh ranah apektif dan psikomotorik.
Muhadjir Effendy pun menyambut harapan tersebut dengan melontarkan ide menambah jam sekolah yang ia istilahkan sebagai Full Day School yang langsung menuai reaksi pro dan kontra masyarakat medsos. Muhadjir memiliki kekhawatiran jeda jam kosong sepulang sekolah sementara kedua orangtua di kota-kota besar belum pulang kerja menjadi pemicu anak- anak tercebur mengakses hal-hal negatif.
Muhadjir hanya melihat kasus di kota-kota besar yang telah memiliki fasilitas yang cukup memadai, guru dan pendamping yang mumpuni, tanpa memperhatikan ribuan sekolah di daerah yang terlantarkan baik dari segi fisik bangunan maupun dari keterbatasan fasilitasnya. Sulit dibayangkan apa yang bisa anak-anak lakukan di sekolah hingga jam 5 sore jika hanya disuruh melihat lapangan gersang dan bangunan sekolah yang hampir roboh didampingi para guru yang kelelahan dan membosankan.
Hemat saya, Muhadjir ketimbang mengetuk palu pemberlakuan Full Day School yang membutuhkan persiapan yang lama dan akan menguras dana yang cukup besar sekaligus diragukan efektivitasnya, lebih baik memberi kekebalan dan perlindungan hukum kepada sekolah sebagaimana PP no 74/2008 tentang guru. agar para guru kembali leluasa melakukan pendekatan kekerasan mengingat kultur orang Indonesia memang mesti dikerasi jika ingin berhasil dibenahi.
Sebagaimana unsur fisik manusia yang terdiri dari segarnya aliran darah, lembutkenyalnya gumpalan daging, serta kerasnya tulang belulang. Jadi, ada kalanya sebagai guru kita mesti menerangkan materi pelajaran dengan mengalir, menasehati kekeliruan siswa dengan lembut, dan memukulnya dengan keras prilaku merusak siswa jika diperlukan. Marah tapi tidak memakai amarah. Bukankah teriak membentak memberi penegasan kepada siswa mesti berakting dengan nada keras, pun misalnya menggebrak meja untuk menggertak siswa juga perlu kekerasan. Sekali lagi keras bukan keji. Keras yes, keji no! Wallahu a’lam. (*)